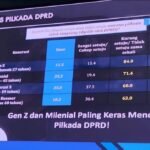Pemerintah boleh saja merayakan penurunan Rasio Gini ke angka 0,375 (BPS, Maret 2025) sebagai kemenangan moral. Namun, bagi siapa pun yang bersedia melihat melampaui statistik permukaan, angka tersebut tak lebih dari kosmetik fiskal. Kita sedang menyaksikan sebuah anomali: perut rakyat bawah sedang “dijinakkan” dengan subsidi, sementara jantung ekonomi nasional semakin terkonsentrasi di tangan segelintir elit.
Paradoks Perut vs Aset
Kebijakan mercusuar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memang efektif menggeser angka pengeluaran di Desil 1 hingga Desil 4. Secara metodologi BPS, saat orang miskin belanja lebih banyak karena uangnya tak lagi habis untuk makan, ketimpangan terlihat membaik. Namun, ini adalah jebakan logika. Memperbaiki ketimpangan konsumsi tanpa menyentuh ketimpangan kepemilikan aset adalah seperti mengobati kanker dengan plester.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per kuartal IV-2025 menjadi bukti telanjang. Di saat pemerintah mengklaim keberhasilan ekonomi, kenyataannya kurang dari 1% pemilik rekening bank di Indonesia menguasai lebih dari 52% total simpanan nasional. Artinya, likuiditas bangsa ini tidak mengalir; ia mengendap di puncak piramida. Sementara itu, mayoritas rakyat (Desil 1-6) hanya memperebutkan sisa “remah-remah” simpanan yang tidak sampai 10% dari total dana perbankan.
Struktur yang Tidak Adil
Laporan World Inequality Database (WID) 2026 menunjukkan potret yang jauh lebih brutal: 10% orang terkaya Indonesia memegang kendali atas hampir 60% kekayaan nasional. Di sektor agraria, ketimpangan ini mencapai level yang menyedihkan. Data Sensus Pertanian (BPS) secara konsisten menunjukkan fenomena “petani gurem” yang terus membengkak, di mana jutaan keluarga petani hidup di atas lahan kurang dari 0,5 hektar, kontras dengan segelintir korporasi yang menguasai jutaan hektar melalui Hak Guna Usaha (HGU).
Hilangnya Sang Penopang: Kelas Menengah
Tajamnya kritik ini juga harus diarahkan pada nasib Kelas Menengah (Desil 5-7). Di era ini, mereka adalah anak tiri pembangunan. Mereka tidak cukup miskin untuk mendapat bansos, namun tidak cukup kaya untuk kebal dari inflasi pendidikan dan kesehatan yang tumbuh dua digit. Fenomena eating savings (makan tabungan) yang tercermin dalam data konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa kelas menengah kita sedang mengalami de-industrialisasi pribadi. Mereka turun kelas demi menjaga angka konsumsi nasional tetap stabil.
Demokrasi yang Terancam
Ketimpangan ekonomi yang ekstrem adalah ancaman langsung bagi demokrasi. Ketika kekayaan terkonsentrasi, kekuatan politik pun ikut terkonsentrasi. Jika Prabowo-Gibran hanya fokus pada program-program “bagi-bagi” tanpa berani menyentuh pajak kekayaan (wealth tax), reforma agraria yang nyata, dan penegakan hukum terhadap monopoli, maka pertumbuhan 8% yang dijanjikan hanyalah akan mempertebal kantong-kantong oligarki yang sudah ada sejak era sebelumnya.
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa di era ini, angka kemiskinan turun bukan karena rakyat mandiri secara ekonomi, melainkan karena mereka “dipelihara” oleh anggaran negara, sementara kedaulatan ekonomi bangsa tetap digenggam oleh segelintir “Naga” yang tak tersentuh radar pajak.***